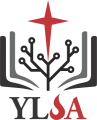ChatGPT dan Kebangkitan AI
2023-08-15 07:39:55

Ketika saya masih remaja, saya membeli komputer pribadi pertama saya yang disebut Timex Sinclair ZX-81 dengan uang yang saya peroleh dari pekerjaan mengantar koran ke rumah-rumah. Saya takjub melihat cara program komputer yang memungkinkan saya membangun -- ide atau rencana yang hampir mustahil terwujud . . . menciptakan dengan pengerahan imajinasi.-1 Sesuatu yang dimulai dari hobi, kemudian berkembang menjadi tugas saat saya mengejar gelar Ph.D. di bidang robotika dan visi komputer. Pada saat itu (hampir 20 tahun yang lalu), bidang AI sedang keluar dari "musim dingin AI" (=periode berkurangnya dana dan minat dalam penelitian kecerdasan buatan, Red.). Saya pun tertarik pada metode pembelajaran mesin yang lebih baru yang sebelumnya digunakan untuk pengenalan gambar.2 Saya ingat betapa saya kagum ketika melihat kecanggihan "melatih" komputer dengan serangkaian gambar contoh dan kemudian mengamati seberapa baik itu dapat mengidentifikasi gambar baru yang bukan bagian dari rangkaian pelatihan yang asli. Bahkan, teknik pembelajaran mesin awal itu tampak ajaib.
Saya mendapati dua hal yang menjadi jelas bagi saya pada tahun-tahun berikutnya. Pertama, teknologi memperkuat peluang untuk berbuat baik, tetapi juga menyebabkan kerugian. Setelah menjadi mahasiswa pascasarjana, saya mengamati banyak upaya penelitian yang diarahkan pada pengenalan wajah — masalah teknis yang menarik dan menantang, tetapi memiliki jebakan untuk penyalahgunaan dan segudang masalah privasi. Saya secara sadar memilih arah penelitian yang menurut saya merupakan aplikasi pembelajaran mesin yang lebih bersifat perbaikan, seperti mengotomatisasikan penyortiran visual barang-barang yang dapat didaur ulang. Saya kemudian mengenali pendekatan ini sebagai peneguhan gagasan teologis tentang struktur dan arah: kemungkinan teknologi berakar pada struktur ciptaan Allah yang baik, sementara arah mengacu pada cara kita mengembangkan teknologi baik dalam ketaatan atau ketidaktaatan kepada Allah.3
Hal kedua yang menjadi jelas bagi saya adalah bahwa AI berkembang lebih cepat daripada yang diperkirakan sebagian besar dari kita. Sebagai seorang mahasiswa pascasarjana teknik sekitar 20 tahun yang lalu, saya akan mencemooh gagasan tentang mobil otomatis. Tantangan visi komputer terlalu besar di lingkungan yang tidak terstruktur dan tidak dapat diprediksi. Dalam dekade tersebut, Google berhasil mendemonstrasikan mobil tanpa pengemudi. Dalam kata-kata Yogi Berra, -Sulit untuk membuat prediksi, terutama tentang masa depan-—bahkan bagi mereka yang sedang mengembangkan teknologi.
Salah satu perkembangan terbaru yang menarik perhatian luas adalah ChatGPT, sebuah chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI. Tidak seperti contoh gambar yang saya gunakan untuk pelatihan dalam tugas pascasarjana saya, ChatGPT menggunakan 570 gigabytes dokumen contoh.4 ChatGPT dapat berinteraksi dengan pengguna dalam menanggapi pertanyaan dan membalas untuk memberi petunjuk (Anda dapat mencobanya di sini). Meskipun beberapa tanggapannya lucu atau salah, hasilnya sering mencengangkan, memberikan tanggapan yang sangat koheren dan meyakinkan untuk berbagai macam petunjuk, termasuk menulis puisi, cerita, khotbah, dan esai. Hasilnya sangat luar biasa sehingga menimbulkan spekulasi tentang esai perguruan tinggi yang sudah mati dan tentang masa depan dari banyak pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Memang, pemrogram komputer mungkin memprogram dirinya sendiri di luar pekerjaannya. Sebuah sistem yang disebut Copilot mengambil input petunjuk dan menghasilkan kode komputer, membuat beberapa orang berspekulasi tentang akhir dari pemrograman.
Meskipun desas-desus tentang matinya esai dan pemrograman kemungkinan besar dilebih-lebihkan, akan ada dampak yang pasti bagi pendidikan tinggi. Bagaimana seharusnya kita memodifikasi tugas menulis dan kebijakan integritas akademik ketika siswa memiliki akses ke teks yang dihasilkan AI? Bisakah kita menggunakan teks buatan AI untuk latihan penilaian kritis yang dapat membantu siswa menulis (dan membuat kode) dengan lebih baik? Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini akan membutuhkan bagian diskusi yang lebih luas, berikut ini adalah tiga pedoman umum saat kita melihat tanggapan orang Kristen terhadap AI.
Pertama, kita perlu menghindari jebakan dari memandang teknologi dengan terlalu banyak optimisme atau pesimisme yang tidak semestinya. Kita harus menolak pandangan dunia reduksionistik yang memandang bahwa semua masalah dapat direduksi menjadi masalah teknis yang dapat diselesaikan oleh teknologi. Kepercayaan pada teknologi, terkadang disebut sebagai teknikisme, pada dasarnya adalah bentuk penyembahan berhala. Di sisi lain, kita tidak boleh melihat perkembangan teknologi dengan keputusasaan bahwa mereka pasti akan mengancam umat manusia. AI adalah bagian dari potensi laten dalam penciptaan, dan kita dipanggil untuk membuka kemungkinannya secara bertanggung jawab. Teolog Al Wolters menulis bahwa -- Alkitab memiliki keunikan dengan tidak mengkompromikan penolakannya terhadap semua upaya . . . untuk mengidentifikasi bagian dari ciptaan itu entah sebagai penjahat atau penyelamat.-5
Kedua, daripada berfokus pada hal yang dapat dilakukan AI, kita perlu memulai dengan pertanyaan ontologis: bagaimana manusia berbeda dari mesin? Kecenderungan umum adalah antropomorfisasi mesin sehingga mengangkat status mesin. Dengan demikian, mengurangi kekhasan manusia. Sejak tahun 1960-an, pelopor AI awal, Joseph Weizenbaum, mengeksplorasi gagasan mengotomatisasi psikoterapi dengan chatbot bernama ELIZA. Weizenbaum menyimpulkan, -Ada batasan untuk segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh komputer.-6 Dalam bukunya, Humans Are Underrated, Geoff Colvin menyarankan untuk mengajukan pertanyaan berikut: -Apa aktivitas yang kita sebagai manusia, didorong oleh sifat terdalam kita atau oleh realitas kehidupan sehari-hari, akan dengan sungguh-sungguh dilakukan oleh manusia lain, terlepas dari apa yang dapat dilakukan komputer?-7 Chatbot atau robot AI tidak boleh menggantikan kebijaksanaan, perhatian, atau persahabatan manusia. Tanpa landasan ontologis yang diinformasikan secara alkitabiah, kita akan rentan terhadap berbagai filosofi reduksionistik, seperti fisikisme dan Gnostisisme.8 Kisah Alkitab jelas bahwa meskipun manusia juga ciptaan, kita diciptakan secara unik menurut gambar Allah dan berbeda dari mesin. Gagasan tentang Imago Dei bertahan, bahkan ketika mesin kita menjadi lebih mampu melakukan hal-hal yang, hingga saat ini, hanya dapat dilakukan oleh manusia. Teolog Herman Bavinck berpendapat bahwa -- manusia tidak membuat atau memiliki gambar Allah, tetapi . . . dia adalah gambar Allah.-9
Ketiga, kita perlu membedakan norma untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab. Pembuat ChatGPT menghadapi masalah "Penyelarasan AI"—tantangan untuk menyelaraskan sistem AI dengan tujuan dan nilai para desainer. Pengembang harus bergulat dengan bias (termasuk rasisme) dalam pengaturan pelatihan mereka. Teknologi tidak netral, begitu pula algoritma dan data pelatihan yang digunakan dalam AI. Akibatnya, sistem AI dapat melestarikan ketidakadilan, ancaman nyata karena "big data" digunakan pada berbagai bidang termasuk asuransi, kepolisian, pemasaran, pinjaman, dan politik.10 Kita perlu membedakan norma penciptaan untuk AI yang mencakup pertimbangan seperti keadilan, kesesuaian budaya, kepedulian, norma sosial, kepengurusan, transparansi, dan kepercayaan.11
Karena norma tidak hanya dapat direduksi menjadi algoritma, kita memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui sejauh mana kita harus mengganti peran konvensional manusia dengan mesin. Selain itu, norma-norma yang tepat seharusnya mengarahkan kita untuk menggunakan AI guna membuka kemungkinan baru dengan tujuan menunjukkan kasih kepada sesama dan memelihara bumi, serta makhluk-makhluknya.12 AI telah menunjukkan penerapan akan adanya perbaikan yang luar biasa dalam pengobatan, penemuan obat, pemantauan lingkungan, pelestarian satwa liar, membantu penyandang disabilitas, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Ilmuwan dan insinyur komputer Kristen dapat menemukan penyebab umum dan bergabung dengan kelompok, seperti AI untuk Kebaikan, AI untuk Bumi, dan AI dan Iman. Selain itu, ilmuwan komputer akan membutuhkan bantuan dari filsuf, teolog, ilmuwan sosial, dan lainnya pada bidang humaniora untuk membantu mengarahkan teknologi, seperti teks yang dihasilkan AI dengan cara normatif (sebenarnya, konteks seni liberal adalah tempat yang ideal untuk kolaborasi semacam itu). 13
Fred Brooks, seorang ilmuwan komputer Kristen yang disegani menulis, -Sudah waktunya untuk menyadari bahwa tujuan asli AI tidak hanya sangat sulit, tetapi juga tujuan yang, meskipun memesona dan memotivasi, menyebarkan disiplin ke arah yang salah.-14 Brooks mengadvokasi sistem IA (Intelligence Amplifying) di atas AI, menyarankan manusia dan mesin akan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada AI saja. Sebagai contoh, salah satu rekan saya di Calvin University telah mengeksplorasi penggunaan AI untuk membantu orang menulis dengan lebih baik (bukan menulis untuk mereka).
Terlepas dari kemungkinan distorsi yang berdosa, AI adalah bagian dari kemungkinan yang menakjubkan dalam ciptaan yang dengan bantuan orang Kristen dapat dipakai untuk memuliakan Allah. Orang Kristen perlu bergabung dalam dialog yang lebih luas seputar teknologi baru yang besar pengaruhnya ini dengan menyatakan pemahaman tentang makna menjadi manusia dan membantu membentuk kebijakan publik dengan preferensi yang alkitabiah dan relevan.15
(t/Jing-jing)
Catatan kaki
- Frederick P. Brooks, The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering (Boston: Addison-Wesley, 1995), 7.
- Saat itu, saya menggunakan sesuatu yang disebut Principal Component Analysis (PCA).
- Albert M. Wolters, Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005), 87–88.
- https://nlp.stanford.edu/pubs/tamkin2021understanding.pdf
- Wolters, Creation Regained, 61.
- Joseph Weizenbaum, Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation (New York: WH Freeman, 1976) 5–6.
- Geoff Colvin, Humans Are Underrated: What High Achievers Know That Brilliant Machines Never Will (New York: Penguin, 2015) 42.
- Derek C. Schuurman, -Artificial Intelligence: Discerning a Christian Response,- Perspectives on Science and Christian Faith 71, no. 2, (Juni 2019): 75–82.
- Herman Bavinck, Reformed Dogmatics: God and Creation, ed. John Bolt, trans. John Vriend (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2004) 554, penekanan pada aslinya.
- Buku bagus yang menyoroti masalah ini adalah Cathy O'Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy (New York: Crown, 2016).
- Saya menjelaskan norma-norma teknologi komputer ini secara lebih rinci di bab 4 Shaping a Digital World: Faith, Culture and Computer Technology (Downers Grove, IL: InterVarsity Academic Press, 2013).
- Derek Schuurman, -Steering a Course for Artificial Intelligence,- The Banner, September 2018.
- Di Calvin, kami merencanakan beberapa percakapan seputar ChatGPT dalam beberapa bulan mendatang.
- Frederick P. Brooks Jr., -The Computer Scientist as Toolsmith II,- Communications of the ACM 39, no. 3, (Maret 1996): 64.
- Komitmen Cape Town yang keluar dari Kongres Lausanne mencakup "seruan untuk bertindak" yang secara khusus mengidentifikasi teknologi baru seperti AI sebagai area dengan "implikasi mendalam bagi Gereja" di mana orang Kristen perlu terlibat.
Diterjemahkan dari:
Nama situs: Christian Scholar’s
Alamat situs: https://christianscholars.com/chatgpt-and-the-rise-of-ai/#easy-footnote-1-10292
Judul asli artikel: ChatGPT and the Rise of AI
Penulis artikel: Derek C. Schuurman
Copyright © 2023 - Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). All Rights Reserved